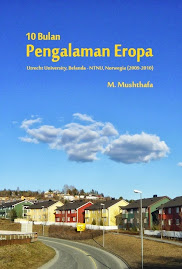Gugatan Etis Simone de Beauvoir terhadap Budaya Patriarkat
Penulis : Shirley Lie
Pengantar : Karlina Supelli
Penerbit : Grasindo, Jakarta
Cetakan : Pertama, 2005
Tebal : xx + 102 halaman
Di kalangan para aktivis gender, Simone de Beauvoir merupakan salah satu tokoh kunci yang pemikirannya tak bisa dilewatkan untuk ditelaah. Magnum opusnya, Le Deuxième Sexe (1949), dicatat sebagai karya klasik yang memberikan uraian cukup komprehensif tentang kondisi (ketertindasan) perempuan dan telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam menginspirasi dan memotivasi gerakan-gerakan pembebasan perempuan. Karya klasiknya itu, yang dalam bahasa Inggris berjudul The Second Sex, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Promethea Yogyakarta (2003).
Buku yang semula adalah tesis di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta ini adalah salah satu dari sedikit karya dalam bahasa Indonesia yang mencoba mensistematisasi dan mengkontekstualkan pemikiran-pemikiran Beauvoir. Gagasan-gagasan Beauvoir yang dapat dikatakan bersifat filosofis dan merupakan kritik pedas terhadap budaya patriarkat yang menindas dalam buku ini diletakkan dalam kerangka praksis-etis pembebasan kaum perempuan. Untuk itu, penulis buku ini, selain mengolah dari The Second Sex, juga banyak mengolah pemikiran filosofis Beauvoir yang tertuang dalam The Ethics of Ambiguity.
Budaya patriarkat memulai riwayat penindasannya terhadap perempuan dengan stigmatisasi negatif terhadap kebertubuhan perempuan. Unsur-unsur biologis pada tubuh perempuan dilekati dengan atribut-atribut patriarkat dengan cara menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah hambatan untuk melakukan aktualisasi diri. Perempuan diciutkan semata dalam fungsi biologisnya saja. Dengan cara demikian, tubuh bagi kaum perempuan tak lagi dapat menjadi instrumen untuk melakukan transendensi sehingga perempuan tak dapat memperluas dimensi subjektivitasnya kepada dunia dan lingkungan di sekitarnya. Tubuh yang sudah dilekati nilai-nilai patriarkat ini kemudian dikukuhkan dalam proses sosialisasi serta diinternalisasikan melalui mitos-mitos yang ditebar ke berbagai pranata sosial: keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan mungkin juga negara.
Dalam kerangka penjelasan seperti inilah maka perempuan kemudian diposisikan sebagai jenis kelamin kedua (the second sex) dalam struktur masyarakat. Akibatnya, perempuan tak dapat mengolah kebebasan dan identitas kediriannya dalam kegiatan-kegiatan yang positif, konstruktif, dan aktual. Dalam situasi yang demikian ini, pola relasi kaum laki-laki dan perempuan menjadi tak ramah lagi. Kaum laki-laki tak menghendaki adanya ketegangan relasi subjek-objek, sebagaimana dijelaskan oleh filsuf-filsuf eksistensial, dengan menyangkal subjektivitas perempuan dan menjadikannya sebagai pengada lain absolut.
Pada titik inilah pemikiran Beauvoir tentang etika ambiguitas menjadi penting dikemukakan. Dengan etika ambiguitas, Beauvoir menolak sikap yang ingin mengelak dari ketegangan relasi tersebut. Menurut Beauvoir, ketegangan antara “kebutuhan akan orang lain” dan “kekhawatiran dikuasai orang lain” (diobjekkan) merupakan situasi yang harus diterima apa adanya dan ditransendensikan ke dalam situasi yang lebih proporsional dan manusiawi.
Jalan pembebasan kaum perempuan ditempuh dari dua jalur utama, yakni level pemikiran dan praktik. Pada tataran pemikiran, tubuh perempuan harus dibebaskan dari label-label yang ditempelkan oleh budaya patriarkat yang membuatnya tak leluasa melakukan proses transendensi. Selain menempatkan konsep subjek dengan tubuh yang berbeda dan ambigu, Beauvoir juga menyerukan untuk mengubah pola relasi antara kaum laki-laki dan perempuan dari ikatan biologis dan fungsional menjadi ikatan manusawi dan etis, yang terangkum dalam semangat persahabatan dan kemurahan hati.
Di level praktik, Beauvoir mengusulkan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai pintu pembuka bagi pembebasan tubuh perempuan, yang akan semakin mantap jika dipadukan dengan perlakuan setara terhadap perempuan di ranah sosial, budaya, dan politik, yang dicapai melalui revolusi sosial.
Selain melakukan sistematisasi, buku ini cukup berhasil melakukan kritik dan kontekstualisasi pemikiran-pemikiran Beauvoir dalam konteks problem-problem kekinian perempuan di era globalisasi. Di beberapa bagian, misalnya, menurut penulis buku ini, Beauvoir kadang terlihat terlalu menyederhanakan persoalan situasi perempuan dan tidak mengakomodasi kompleksitas situasi penindasan perempuan yang cukup rumit. Di akhir bagian, penulis buku ini menambahkan bahwa selain ancaman nilai-nilai patriarkat sebagaimana tampak jelas dalam pemikiran Beauvoir, perempuan kini juga ditantang oleh kekuatan pasar bebas yang untuk beberapa hal tak jauh berbeda dengan kultur patriarkat dalam soal menyempitkan ruang perempuan ke dalam kategori objek belaka, di tengah kegamangan kaum perempuan untuk terjun ke dalam ketegangan dan sifat dasar kebebasannya.
Karya ini cukup berhasil menyajikan pemikiran-pemikiran filosofis Simone de Beauvoir tentang praksis etis pembebasan perempuan dalam bahasa dan uraian yang cukup mudah dicerna tanpa harus kehilangan segi kedalaman kajiannya. Buat mereka yang terjun di level gerakan (sosial) pembebasan perempuan, buku ini dapat menyuguhkan peta umum kondisi perempuan dengan berbagai kompleksitas persoalannya, dan buat kaum perempuan sebagai individu, Beauvoir melalui karya ini memberikan semangat dan seruan untuk hidup lebih autentik dan hidup dengan menggali identitas dan kebebasannya.
* Tulisan ini dimuat di Jurnal Perempuan edisi 45, Januari 2006