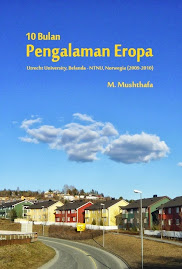Judul Buku: Pergulatan Muslim Komunis (Otobiografi Hasan Raid)
Judul Buku: Pergulatan Muslim Komunis (Otobiografi Hasan Raid)
Penulis : Hasan Raid
Penyunting: M. Imam Aziz (dkk.)
Penerbit: LKPSM-Syarikat, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Februari 2001
Tebal: x + 558 halaman
Dendam terhadap kaum komunis (baca: PKI) belum juga sirna. Dalam beberapa peristiwa politik yang melibatkan aksi kekerasan, orang-orang komunis kerapkali dituding sebagai pelakunya. Beberapa elemen gerakan mahasiswa sempat diteror oleh sekelompok orang yang mengaku hendak menumpas habis komunisme di Indonesia.
Akankah dendam politik terhadap PKI tidak akan pernah luntur, kecuali menghabisi mereka tanpa ampun, tanpa proses pengadilan, tanpa menghargai mereka sebagai manusia yang menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia? Akankah agama akan tetap dijadikan dalih untuk membenarkan sikap anarkis terhadap PKI?
Buku ini menawarkan suatu perspektif menarik tentang salah seorang tokoh PKI yang sempat dipenjara selama hampir 13 tahun. Hasan Raid, aktivis PKI kelahiran Silungkang Sumatera Barat ini, adalah sosok unik yang sanggup mematahkan kebuntuan paradoks agama dan komunisme.
Dalam otobiografinya ini Hasan Raid menjelaskan bahwa alasannya memilih masuk Partai Komunis Indonesia pertama-tama adalah karena PKI merupakan partai yang dalam programnya berjuang untuk menghapuskan penghisapan manusia atas manusia.
Program ini, menurut Hasan Raid, memiliki kesesuaian dengan semangat agama (Islam) yang ia yakini. “Ajaran Pokiah Yakub, guru Sekolah Diniyah di Silungkang, yang paling berkesan bagi saya adalah ajaran beliau tentang surat al-An`am ayat 145, tentang hukum haram memakan darah yang mengalir,” kata Hasan Raid. “Tidakkah penghisapan sesama manusia itu adalah persamaan dari terminologi al-Qur’an, memakan darah mengalir?,” lanjut Hasan Raid. Islam menurut Hasan Raid jelas-jelas memiliki banyak kesesuaian dengan program PKI yang ingin menuntas habis kaum kapitalis. Al-Qur’an surat al-Humazah ayat 1-3 mengutuk keras orang yang menumpuk-numpuk harta—itulah kaum kapitalis.
Kaum tertindas menurut Hasan Raid harus mengorganisasi diri melawan struktur penindasan yang menjepit dan menindih kehidupan mereka. Itulah maksud ayat 11 surat al-Ra`d yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.”
Hasan Raid dilahirkan pada tahun 1923 dan secara resmi menjadi anggota PKI pada tahun 1945. Selang beberapa kemudian, Hasan Raid terlibat aktif dalam salah satu penerbitan PKI, yakni Majalah Bintang Merah yang dipimpin Aidit. Selain itu, Hasan Raid juga sempat menjadi anggota DPRDP (DPRD Peralihan) Jakarta Raya (1954-1964) serta menjadi salah seorang pengajar di Akademi Ilmi Sosial Aliarcham (AISA), sebuah lembaga pendidikan tempat penggodokan para intelektual PKI.
Suka duka yang dialami Hasan Raid selama di PKI berjalan seiring dengan roda sejarah perkembangan bangsa Indonesia, hingga akhirnya meletuslah peristiwa Gerakan 30 September, yang lebih populer disebut dengan G-30-S.
Pada bagian ini, tampak sosok Hasan Raid yang teguh dengan pendirian dan keyakinannya, serta tidak segan-segan melakukan otokritik terhadap kebijakan-kebijakan partai (PKI). Ketika diinterogasi Kodim Jalan Air Mancur Jakarta Raya selepas peristiwa G-30-S Hasan Raid jelas-jelas mengutuk peristiwa itu. “G-30-S adalah ‘kudeta’, bukan revolusi. Sebab kudeta asing bagi marxisme,” kata Hasan Raid.
Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan Hasan Raid kemudian, muncullah suatu kesimpulan bahwa menurutnya G-30-S bukan merupakan pemberontakan PKI. Bila itu adalah pemberontakan PKI, berarti PKI memberontak kepada pemerintahan Presiden Soekarno, presiden yang jelas-jelas mendukung pemikiran dan keberadaan PKI. Apalagi, menurut keputusan Kongres Nasional V PKI 1954 dikatakan bahwa untuk mencapai demokrasi rakyat PKI akan menempuh jalan demokratis dan parlementer, bukan dengan pemberontakan atau perjuangan bersenjata.
Karena itu, sampailah Hasan Raid pada kesimpulan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi peristiwa G-30-S. PKI menurut Hasan Raid telah terjebak dalam isu Dewan Jenderal sehingga kemudian harus memilih antara didahului atau mendahului. Keterjebakan PKI ini jelas merugikan PKI sendiri, hingga ujungnya melahirkan tragedi besar berupa pembantaian anggota PKI serta dijebloskannya anggota PKI yang lain ke penjara.
Hasan Raid adalah termasuk orang yang dijebloskan ke dalam penjara beberapa minggu sesudah peristiwa G-30-S. Selanjutnya, kisah Hasan Raid adalah kisah kepedihan kehidupan di penjara. Hampir separuh bagian dari buku ini menceritakan suka-duka kehidupan di penjara yang dijalaninya selama hampir 13 tahun di bawah rezim Orde Baru, mulai dari Rumah Tahanan Chusus Salemba, hingga kemudian dipindahkan ke Nusakambangan.
Perlakuan buruk di penjara bagi para tahanan politik mungkin sudah menjadi cerita lama yang tidak menarik diceritakan. Yang cukup mengharukan pula adalah bagaimana setelah Hasan Raid bebas dari penjara pada tahun 1978 menjalani kehidupannya sehari-hari. Penderitaan dan ketidakadilan masih saja membuntutinya.
Seiring dengan kontrol kuat rezim Orde Baru terhadap gejolak-gejolak politik dan ideologi, maka para bekas tahanan politik mendapat pengawasan ekstra-ketat dari negara. Ruang publik menjadi tempat yang cukup pengap sehingga menghadapkan Hasan Raid pada sebuah pergulatan keras untuk survive. Pada bagian ini, ada banyak sisi kemanusiaan yang mengemuka dalam otobiografi ini.
Buku ini adalah suara lain dari pihak yang dibungkam oleh Orde Baru selama lebih dari 32 tahun. Citra buruk terhadap para mantan aktivis PKI masih belum sirna. Ironisnya, label PKI masih cukup laku dalam kamus politik di era reformasi ini. Politik kambing hitam yang mengusung semangat dendam politik berkepanjangan masih tak usai dipertontonkan.
Tidak adakah jalan lain yang bisa ditempuh untuk mengakhiri dendam kecuali harus dengan permusuhan dan pemusnahan? Tidak bisakah kita berdamai dengan sejarah dan memulai hidup baru yang lebih damai? Tidak bisakah kita hidup lebih rasional terhadap sejarah yang selama ini dimitoskan dan menjadi ajang pembenaran untuk mengumbar dendam?
Buku ini mengajarkan banyak kearifan tentang kehidupan politik yang saat ini kehilangan wajahnya yang manusiawi. Ada pesan bijak buat para elti politik yang terselip dalam buku ini: sudah saatnya dendam dan kebencian yang didorong oleh ambisi kekuasaan dienyahkan jauh-jauh, digantikan dengan sikap arif, jernih, dan rasional. Maksud dari semua ini cukup sederhana: menuju rekonsiliasi nasional.
Kamis, 10 Mei 2001
Menuju Rekonsiliasi Nasional
Label: Book Review: Social
Jumat, 04 Mei 2001
Meneguk Spiritualitas New Age
 Judul Buku : New Age: Wisata Spiritual Lintas Agama
Judul Buku : New Age: Wisata Spiritual Lintas Agama
Penulis : Sukidi
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Cetakan: Pertama, 2001
Tebal: xii + 152 halaman
Krisis pengenalan diri manusia modern telah lama ditengarai Ernst Cassirer dalam bukunya, An Essay on Man yang terbit pada tahun 1944. Awal dekade 1960-an, pemikir-pemikir dari Mazhab Frankfurt—seperti Adorno, Horkheimer, atau Marcuse—juga mencium suatu krisis eksistensial manusia modern akibat paradigma teknologis sains yang mekanistik.
Ada yang menyebut abad ini sebagai abad kecemasan (the age of anxiety), ketika seluruh sisi kehidupan manusia—sosial, budaya, lingkungan, bahkan agama— terancam oleh apa yang dihasilkan manusia sendiri.
Kekecewaan mendalam terhadap fenomena krisis eksistensial-multidimensional ini memunculkan beragam bentuk gerakan sosial dan pemikiran baru yang berusaha mengobati alienasi hidup manusia modern.
Gerakan New Age adalah salah satu gerakan pemikiran yang berusaha menawarkan suatu cara baca baru dalam memahami realitas dengan pijakan utama pemikiran-pemikiran dari tradisi Filsafat Perennial. Menurut pembacaan para pemikir New Age, seperti Seyyed Hossein Nasr, masyarakat modern sebenarnya telah kehilangan visi keilahiannya dalam memaknai realitas hidup. Visi tersebut menjadi tumpul ketika mereka telah menjadi pemuja sains dan teknologi yang pada satu sisi mereduksi integritas hakikat manusia ke dalam suatu sistem rasionalitas yang tidak manusiawi.
Dengan paradigma sains yang mekanistik dan materialistik manusia selalu dirangsang berpikir bagaimana mengeksploitasi alam tanpa harus berpikir tentang bagaimana keseimbangan ekologis harus tetap terjaga.
New Age secara paradigmatik berusaha mendefinisikan kembali makna “kesucian” (redefining of the sacred) dengan sekaligus mensakral-ulangkan bumi, manusia, dan hidup sehari-hari. Untuk itu, New Age turut berusaha mengembalikan hakikat kedirian manusia yang integral dengan cara melirik dan merangkum berbagai tradisi pemikiran dari berbagai latar agama dan kebudayaan yang berbeda-beda. Perspektif perennial terhadap pelbagai tradisi spiritual itu berhasil menyatukannya dalam suatu wilayah esoteris yang mencoba memaknai keragaman bentuk sebagai sesuatu yang bersifat alamiah.
Fitrah manusia yang asasi seperti keadilan, kebenaran, kebersamaan, toleransi di tengah pluralitas, dan sebagainya berusaha dicari dan ditemukan kembali dalam tradisi-tradisi spiritual lintas budaya dan agama. Kalangan New Age enggan kembali kepada pemikiran agama-agama formal, karena dinilai cenderung eksklusif, eksoteris, bahkan ‘palsu’ (false).
Dalam pandangan pemikiran New Age, konsep keselamatan yang ditawarkan agama-agama formal telah menghilangkan perspektif kearifan dan kedamaian agama, sehingga tidak jarang melahirkan fanatisme, sektarianisme, atau bahkan perang atas nama agama. Klaim keselamatan melahirkan sikap ketertutupan terhadap kebenaran dari tradisi lain.
New Age lebih tertarik percaya pada prinsip Enlightenment (Pencerahan). Manusia diyakini dapat tercerahkan, lalu menjadi sacred self, kembali ke fitrahnya semula. Dan, untuk meraih pencerahan, New Age percaya bahwa ada banyak jalan yang bisa dilalui. Setiap agama yang berbeda-beda pada dasarnya adalah jalan-jalan menuju Tuhan yang pada ujungnya akan memiliki titik temu dalam medan esoteris agama, yakni Tuhan.
Dalam wilayah yang lebih luas muncul kesadaran untuk meyakini bahwa setiap jalan kehidupan membuka peluang untuk memberikan ‘petuah’ kebijaksanaan. Buku-buku dengan judul frase The Tao of… yang merambah bidang ekonomi, pendidikan, agama, musik, politik, atau kesehatan, mengindikasikan hal ini.
Kebangkitan spiritual baru ala New Age tidak hanya diikuti dengan bermunculannya buku-buku dengan paradigma The Tao of…tersebut. Tercatat pula sebuah trilogi karya James Redfield—The Celestine Prophecy, The Tenth Insight, dan The Secret of Shambala—yang kabarnya telah mengubah hidup banyak orang. Dalam ketiga novel tersebut digambarkan bagaimana peradaban manusia berjalan menuju suatu kebudayaan spiritual baru.
Tawaran paradigmatik New Age ini menjadi menarik karena cukup berhasil meyakinkan banyak orang bahwa ini adalah cara paling tepat untuk menyelesaikan persoalan personal dan sosial akibat krisis kebudayaan manusia. New Age berusaha mentransformasikan kesadaran personal untuk kemudian meluas dalam wilayah sosial. Dalam pandangan New Age, perubahan menuju kebudayaan spiritual harus dimulai dari aras personal.
Wisata spiritual—demikian istilah Sukidi—lintas agama dan budaya adalah petualangan yang menantang dan membutuhkan keberanian. Bukan untuk menaklukkan tradisi lain, tetapi menimba kebijaksanaan, kemudian kembali lagi ke rumah tradisi semula.
Buku ini mengajak pembaca untuk menggali kembali kesadaran-kesadaran kemanusiaan yang bersifat fitri yang tertimbun oleh jejal sampah modernitas, mengaisnya ke permukaan dan kemudian menebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Berbagai kebijaksanaan fitri itu sebenarnya berada di mana saja, dalam semua tradisi spiritual dan kebudayaan manapun di dunia ini, sehingga pada akhirnya secara tidak langsung buku ini juga mengajak kita untuk secara intens saling bertegur sapa dan bertukar pikiran dengan orang lain yang berasal dari latar kebudayaan dan spiritualitas yang berbeda.