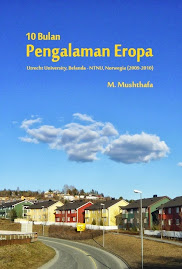|
| Sumber gambar: Wikipedia |
lf you wanna sell a lie, you get the press to sell it for you.
- Lester Siegel, Argo (2012)
Adakah orang yang mau membeli dusta? Rasanya tidak ada. Namun tanpa sadar, kadang kita tak merasa bahwa kita sedang melahap dusta—dengan kadar atau takaran yang berbeda.
Lalu di mana orang-orang kadang tanpa sadar melahap dusta? Kutipan dari film terbaik Academy Award 2013 di atas memberi kita jawabannya. Dalam kutipan dari film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan peristiwa penyelamatan sandera diplomat Amerika di Teheran dalam kemelut politik di Iran tahun 1979 itu, kita menemukan kekuatan media (pers) dalam menyebarkan dusta.
Kutipan di atas memang tampak cenderung menunjukkan unsur emosi yang tidak netral. Mungkin terkesan sinis. Atau hiperbolis. Jika mau ditarik ke dalam ungkapan yang lebih netral, kutipan di atas mungkin menyimpan proposisi lain yang mendahuluinya: yakni bahwa kekuatan media (pers) itu sedemikian besar. Dengan demikian, jika ada niat untuk menyebarkan kebohongan maka media menyediakan tempat yang efektif.
Dalam kutipan di atas, dusta yang dibicarakan adalah dusta yang disengaja— dusta yang dirancang untuk tujuan tertentu. Dalam konteks Argo, dusta itu adalah tipu daya untuk mengelabui pemerintah Iran demi menyusupkan tim penyelamat diplomat Amerika ke Iran dengan berkedok kru film fiksi-sains dari Hollywood.
Namun, dusta atau “perkataan yang tidak benar” juga tetaplah berbahaya meski ia tidak disengaja. Apalagi ia kemudian disebarkan melalui media dan bisa menyasar pembaca dengan jumlah puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan lebih.
Di tengah semakin maraknya media massa dan sarana penerbitan bagi perorangan di era internet ini, maka judul di atas tak lain adalah pengingat untuk saya dan mungkin juga orang lain bahwa saya haruslah berhati-hati untuk jangan sampai menjadi penjaja dusta di berbagai bentuk lapak informasi.
Bentuk dusta dalam penyebaran informasi di sini bisa sangat sederhana, misalnya berupa posting atau komentar di media sosial seperti Facebook atau Twitter. Yang lebih rumit, wujudnya berupa tulisan yang secara umum dipandang sebagai “berita”.
Berita yang memuat dusta juga bisa diperinci bentuk-bentuknya. Bisa karena fakta yang dihimpun tidak diperiksa dengan ketat, atau karena si penulis tidak cermat menulis kata atau kalimat sehingga apa yang ditulis dan kemudian disiarkannya itu tak sama dengan maksud yang ada di kepalanya.
Untuk soal yang terakhir ini, agar tidak terlalu abstrak, izinkan saya mengangkat contoh sederhana. Jika ada kalimat seperti ini: “Kemarin saya melihat pasangan pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah duduk-duduk di salah satu warung di Pasar Ganding selepas zuhur,” maka pikiran saya akan mengatakan bahwa kedua pelajar yang dimaksud sama-sama mengenakan seragam sekolah. Jika faktanya yang mengenakan seragam hanya salah satunya, maka rasanya tidak salah untuk mengatakan bahwa kalimat di atas memuat dusta.
Apabila pada tulisan yang sama kemudian muncul kalimat seperti ini: “Pak Ahmad heran mengapa dua pasangan pelajar itu sudah ada di Pasar Ganding, padahal saat itu masih jam sekolah,” maka sebagai pembaca saya akan heran dan bertanya-tanya: apakah yang duduk-duduk di warung itu sebenarnya 2 orang ataukah 4 orang?
Istilah “penjaja dusta” pada judul di atas mungkin akan terdengar hiperbolis. Tapi menurut saya, dalam konteks media dan arus informasi yang sedemikian cepat di era internet ini, rasanya tidaklah berlebihan untuk memberikan unsur hiperbolis pada judul tulisan ini. Alasannya, dampak informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan (dusta) itu bisa tak berhingga. Teknologi salin-tempel memudahkan percepatan penyebaran informasi dengan berbagai media, terutama melalui jejaring sosial di internet.
Film Mad City (1997) yang dibintangi oleh Dustin Hoffman dan John Travolta kiranya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana dusta yang dikelola dalam industri media bisa memberikan dampak yang mematikan. Film itu menceritakan kasus salah tembak satpam yang baru dipecat di sebuah museum pada mantan rekan kerjanya yang membuat ia terlibat masalah pelik. Karena keadaan, akhirnya ia “terpaksa” menyandera sekelompok murid sekolah di museum itu. Kasus ini dimanfaatkan oleh sejumlah media sehingga akhirnya membawa sejumlah dampak yang tak terkira.
Jika media diakui memiliki dampak yang begitu dahsyat, apa yang bisa kita lakukan? Untuk selamat dari potensi cap sebagai “penjaja dusta”, setidaknya kita bisa menggarisbawahi kembali hal-hal mendasar dalam kaidah jurnalistik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
Pertama, sesederhana apa pun, pastikan untuk memeriksa kembali fakta-fakta yang sudah dihimpun dari berbagai sumber. Pastikan bahwa fakta-fakta itu memang akurat. Kedua, pastikan bahwa kita sudah menghimpun fakta dan pendapat dari sisi yang lengkap. Jangan sampai ada subjek kunci dalam berita atau peristiwa yang kita tulis tidak mendapatkan tempat untuk bersuara. Ketiga, pastikan bahwa kata-kata atau kalimat yang kita gunakan benar-benar menggambarkan gagasan, pikiran, fakta, atau data yang kita himpun. Jangan bosan untuk membuka kamus untuk memastikan ketepatan makna kata-kata tertentu. Penyuntingan oleh pihak lain mungkin akan membantu jika ada hal-hal penting yang terlewatkan.
Dari sisi lain, sebagai pembaca kita mungkin harus juga membuka kemungkinan bahwa bisa jadi tulisan yang kita cerna di media dalam pengertian yang luas berpotensi untuk memuat dusta. Karena itu, menjadi pembaca yang cerdas dan kritis tampaknya menjadi keharusan di tengah derasnya banjir informasi yang mendera kita saban hari.
Sungguh sedih membayangkan jika generasi kita dibanjiri dengan berita-berita yang memuat dusta. Itu sebuah pembiasaan yang sangat tidak baik dan mungkin berpeluang untuk meracuni pikiran dan cara pandangnya dalam melihat peristiwa dan dunia.
Khususnya mereka yang suka menulis di berbagai media, dari yang sederhana hingga yang profesional, mari kita terus berupaya untuk berlindung dari menjadi orang yang termasuk dalam kelompok penjaja dusta. Sebagai pembaca, mari kita menjadi pembaca yang cerdas dan kritis.
Baca juga:
>> Bila Media Tak Setia pada Fakta
>> Melek Informasi