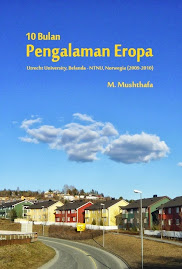Pembicaraan masalah seksualitas di ruang publik pada umumnya dipandang sebagai topik yang tabu. Akan tetapi, seiring dengan gerak roda zaman, persepsi semacam ini mulai berubah. Masyarakat
Respons masyarakat terhadap terbitnya buku semacam ini bukan satu-satunya indikator tentang bergesernya tema seksualitas dari wilayah privat ke wilayah publik. Jika kita menelisik halaman demi halaman buku tersebut, atau buku sejenis, kesimpulan kita ini akan semakin kuat. Apa yang diceritakan secara cukup detail dalam buku yang cetak ulung puluhan kali ini adalah realitas kehidupan
Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebenarnya menjadi latar bagi terbukanya wacana dan praktik seksual semacam itu? Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa sikap hidup permisif yang menjadi salah satu bagian dari fenomena modernitas adalah salah satu kunci utamanya. Di negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa, revolusi seksual yang melanda ditandai dengan fenomena semacam itu, mulai dari kehamilan remaja, aborsi, kelahiran anak di luar nikah, bahkan juga AIDS. Modernitas di sini tentu bukan semata menyangkut transformasi sosial-ekonomi masyarakat, tapi juga proses-proses sosio-kultural melalui proses global yang lambat laun mendefinisikan ulang berbagai pandangan dunia tentang beberapa aspek filosofi hidup, relasi manusia, dan sebagainya.
Konstelasi global saat ini telah dengan sangat leluasa menyebarluaskan perangkat-perangkat modernitas ke berbagai pelosok. Maka tak heran jika fenomena seksualitas seperti yang dikisahkan dalam Jakarta Undercover itu perlahan juga terjadi di pulau Madura. Beberapa waktu yang lalu, misalnya, sempat heboh rekaman video mesum yang beredar di wilayah Bangkalan dan disebut-sebut diperankan oleh gadis lokal (detikSurabaya, 5/10/2008). Dalam berita yang lain, sering kita dengar razia telepon genggam di sekolah yang menunjukkan bagaimana siswa mengoleksi video-video biru—bahkan mungkin juga guru.
Kasus tersebut membuka kesadaran kita bahwa memang benar perangkat teknologi di satu sisi dapat melahirkan perubahan sosio-kultural yang cukup berarti. Tak salah dikatakan bahwa praktik seks bebas atau yang serupa memang mungkin terjadi tanpa bantuan perangkat teknologi. Akan tetapi, perangkat teknologi telah memungkinkan meningkatnya peluang, benih, dan juga persebaran praktik seks bebas dalam wilayah publik yang lebih luas. Sebuah data, misalnya, mengungkapkan bahwa setiap detik 28.258 pengguna internet membuka situs pornografi. Data yang lebih spesifik mengungkapkan bahwa 78 % pelajar di
Madura yang selama ini selalu diidentikkan dengan religiositas atau keislamannya yang kental mau tidak mau juga harus berhadapan dengan masalah ini, yakni semakin meluasnya praktik seksualitas yang terbuka. Jika kita sepakat bahwa identitas kemaduraaan yang disandingkan dengan kentalnya nilai keagamaan adalah sesuatu yang masih berharga secara kultural, maka berarti jika fenomena keterbukaan praktik seksual itu tetap dibiarkan, masyarakat Madura sebenarnya sedang berjalan menuju proses bunuh diri kultural yang mencampakkan nilai-nilai agung yang dimilikinya.
Dalam kajian antropologis, masyarakat Madura dikenal dengan konsep “harga diri”, yang menurut A. Latief Wiyata (2002) menjadi salah satu kunci konseptual untuk memahami kasus carok. Dalam konsep harga diri tersebut, posisi perempuan cukup sentral. Perempuan dipandang sebagai salah satu simbol harga diri. Maka dari itu, mengganggu istri orang lain adalah dosa terbesar yang hanya bisa impas bila dibayar dengan kematian. Bersanding dengan konsep harga diri adalah konsep “malo”. Pelecehan harga diri dalam kultur Madura dimaknai seperti dalam kasus ketika seseorang dianggap tidak diakui atau diingkari kapasitas dirinya sehingga dia merasa tada’ ajina (tidak ada harganya).
Nah, praktik seks bebas, bagaimanapun, di satu sisi dapat dilihat sebagai dekonstruksi atas konsep sakral perempuan yang identik dengan harga diri. Inilah sikap permisif yang memang cukup khas dengan fenomena masyarakat modern.
Mengapa masyarakat Madura yang religius dan memiliki sekian banyak lembaga sosial pendukung yang bertugas menjaga religiositasnya itu saat ini menghadapi tantangan yang sedemikian akut? Salah satu hipotesis yang bisa diajukan adalah berkaitan dengan perubahan peran keluarga di Madura. Keluarga pada dasarnya adalah pusat sosialisasi dan pusat nilai tempat ditanamkannya nilai-nilai kemaduraan. Seperti yang juga terjadi di masyarakat yang lain, tak hanya di kelompok masyarakat tradisional, lembaga keluarga saat ini menghadapi tantangan yang sedemikian berat. Modernitas dan globalisasi telah membuatnya menjadi sedemikian rapuh dan menceraiberaikan ikatan di antara para penghuninya. Karena itu, keluarga kemudian tak lagi menjadi tempat sosialisasi primer lagi dalam masyarakat.
Keluarga yang oleh sebagian kalangan digambarkan sebagai bahtera yang hampir karam ini dalam konteks Madura di antaranya juga dipengaruhi oleh pola pemukiman yang cenderung berubah. Jika dilihat lebih dekat, pola pemukiman yang dominan di Madura yang disebut dengan tanean lanjeng cenderung menempatkan para anggota keluarga dalam tingkat keakraban yang cukup kuat. Berubahnya pola pemukiman yang mengarah para pola individualistis di Madura diakui atau tidak juga berpengaruh pada mulai tumbuhnya sikap acuh tak acuh terhadap anggota keluarga lainnya, termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan soal moral atau seksualitas.
Di sisi yang lain, otoritas keluarga sebagai media pewarisan nilai saat ini telah digerogoti oleh sumber-sumber informasi dan pengetahuan lainnya yang otomatis juga memiliki—atau paling tidak, memberi implikasi—nilai-nilai kultural tertentu. Informasi dan pengetahuan tentang seksualitas, misalnya, saat ini begitu mudah diakses melalui buku-buku atau media penerbitan lainnya, media audio-visual, media interaktif seperti internet, dan sebagainya, yang memang diproduksi secara masif. Apalagi, kita tahu, bahwa selama ini pendidikan seks masih menjadi sesuatu yang tabu. Artinya, dalam keluarga di Madura ataupun dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal, pendidikan seks masih belum diberikan secara khusus. Mungkin ini berkaitan dengan asumsi bahwa seksualitas identik dengan hal yang tak memiliki aspek positif.
Dari gambaran ini, kita dapat mengajukan pertanyaan pamungkas: siapa yang sebenarnya dapat memainkan peran kunci untuk menjawab tantangan seks bebas yang mungkin bisa semakin meluas di Madura? Bagaimana jalan keluar yang baik? Di zaman yang sedemikian rumit ini, tentu sulit menemukan jalan keluar yang tak melibatkan pihak-pihak dalam wilayah yang lebih luas. Jalan keluar yang instan tentu bukanlah jawaban cerdas, karena modernitas dan globalisasi masih menyimpan banyak senjata rahasia yang pasti lebih dahsyat untuk merontokkan solusi instan yang kita buat itu. Bagaimanapun, kita semua harus dapat terlibat dalam ikhtiar menjawab tantangan kultural ini. Penguatan lembaga-lembaga kultural dan nonformal yang memiliki basis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah kerangka dasar kerja budaya untuk menyelamatkan kekuatan budaya masyarakat Madura. Dan ini tak lain berarti penguatan otonomi kultural masyarakat Madura di tengah gegar budaya yang terus datang bertubi.
Wallahualam.
Tulisan ini dimuat di Radar Madura, 19 Januari 2009.