 Judul Buku : Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi
Judul Buku : Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi
Penyunting : Donald K. Emmerson
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Cetakan : Pertama, 2001
Tebal : xxx + 678 halaman
Era transisi bangsa Indonesia menuju kehidupan demokrasi ternyata masih dijejali oleh setumpuk persoalan. Krisis ekonomi yang belum pulih, kerusuhan sosial, konflik vertikal dan horizontal mengiringi pertikaian elit politik, serta ancaman disintegrasi. Tidakkah itu semua merupakan ekses buruk dari “Sistem Soeharto” yang telah berkuasa selama 30 tahun di Indonesia?
Rezim Soeharto telah cukup mampu membentuk suatu struktur mapan yang cukup kokoh di berbagai bidang kehidupan—sosial, politik, ekonomi, budaya, dan yang lain—sehingga lengsernya Soeharto tidak serta merta berarti runtuhnya sistem itu.
Buku ini mencoba menelaah perjalanan panjang bangsa Indonesia di bawah Sistem Soeharto dengan titik tekan pada aspek kenegaraan, ekonomi, dan (budaya) masyarakat, serta bagaimana itu semua menyisakan garis kontinu dalam momen-momen reformasi.
Kelahiran Orde Baru pasca peristiwa G-30-S dimulai dengan suatu komitmen yang kuat untuk menghindari konflik-konflik ideologi, karena itu dianggap akan menyuburkan ladang konflik dan membawa rakyat dalam suatu bayang-bayang keterpecahan sehingga mengancam proses tercapainya cita-cita “modernitas” Indonesia. Orde Baru lebih memilih jalan yang mereka anggap rasional-pragmatis: develomentalisme. Orde Baru tidak mau mengganggap bahwa pilihan mereka ini—penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai prinsip penting developmentalisme—sebagai persoalan ideologi.
Istilah “Demokrasi Pancasila” yang digunakan Orde Baru menurut R. William Liddle dalam buku ini hanyalah penipuan belaka. Orde Baru pada dasarnya tersusun oleh seperangkat lembaga otoriter yang mengekang partisipasi rakyat. Partisipasi yang dikontrol ini sebenarnya adalah konsekuensi logis dari strategi pembangunan ekonomi yang memerlukan stabilitas sosial yang kokoh. Politik massa mengambang yang merupakan wujud kebijakan depolitisasi massa Orde Baru dibarengi dengan sentralisasi kekuasaan negara.
Kontrol negara juga dilakukan dengan sentralisasi kekuasaan, dengan melibatkan militer sebagai penjaga gawang stabilitas. Sentralisasi ini juga diterapkan dalam bidang administratif, legal, dan finansial. Akibatnya, pemerintah daerah tak berdaya memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya. Daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk dikerahkan pada proyek pembangunan. Efek lainnya adalah bahwa orientasi pemerintah daerah tidak lagi mengarah kepada rakyatnya sendiri, melainkan pada pimpinan negara (yakni Soeharto).
Yang menarik, seperti dicatat oleh Michael Malley (Ohio University), dalam rezim Orde Baru sendiri sempat muncul beberapa ketegangan antara pusat dan daerah. Salah satu kasus yang menjadi contoh di buku ini adalah kasus pembelotan anggota Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Tengah dalam pemilihan Gubernur pada tahun 1993 yang menginginkan calon putra daerah diangkat menjadi Gubernur—yang berbeda dengan “petunjuk” dari Jakarta.
Sentralisasi ini dalam beberapa kasus telah berkembang menjadi semacam gerakan “pemberontakan” daerah terhadap pusat kekuasaan akibat ketidakadilan ekonomi yang dirasakan begitu kuat. Kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang muncul sejak 1976 menjadi contoh yang amat tepat dan dibahas secara menarik oleh Malley. Pemberontakan ini, seperti juga pemberontakan oleh PRRI pada akhir 1950-an, awalnya lebih bertujuan untuk mengubah sifat sentralistik republik, bukan untuk lepas dari kesatuan republik.
Kecanggihan “Sistem Soeharto” dalam mengelola rezim adalah bahwa semua itu dilakukan dengan legitimasi konstitusional yang cukup kuat. Dalam Sistem Soeharto konstitusi memang hanya menjadi abdi kekuasaan. Kenyataan ini akhirnya berdampak besar terhadap kegiatan perekonomian negara, dengan terbentuknya model “kapitalisme kroni”. Ketika pasar tidak menentu yang diikuti dengan ketidakpastian politik, ekonomi dan hukum, maka para pengusaha lebih memilih untuk membangun jaringan ekonomi perkoncoan dengan para pemegang kekuasaan.
Akan tetapi, akhirnya Soeharto turun pada 21 Mei 1998. Menurut Donald K. Emmerson, turunnya Soeharto salah satunya dipicu oleh ambruknya bangunan ekonomi yang dibangun selama 30 tahun. Arah globalisasi sebenarnya mengharuskan adanya keseiringan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Tapi Soeharto malah menghalangi modernisasi politik sehingga akhirnya remuklah sistem yang ia bangun itu. Hancurnya perekonomian ini lalu diikuti pula oleh desakan mundur dari massa di bawah dan para kolega politiknya yang juga merasa tertekan.
Ketika Soeharto turun boleh jadi bangsa Indonesia merasa lega karena salah satu penghalang demokratisasi sudah disingkirkan. Namun patut dicatat bahwa bahaya laten Orde Baru—Sistem Soeharto—masih kuat membayangi kehidupan bangsa ini. Ia sudah mengendap secara sistemik dalam berbagai ruang kehidupan bangsa Indonesia.
Dalam konteks inilah buku ini memiliki makna penting dan nilai relevansinya. Sistem otoriter Orde Baru, yang nyaris dikutuk habis-habisan oleh para tokoh reformis, ternyata dibangun dengan suatu karakter tokoh yang amat dominan, yakni Soeharto, yang mengkristal dan mengendap sedemikian rupa sehingga menubuh dalam struktur kesadaran dan struktur sosial-politik bangsa Indonesia. Saking besarnya pengaruh Soeharto sehingga persoalan yang dihadapi saat ini bukan cuma soal bagaimana Indonesia Beyond Soeharto, tetapi juga fakta perihal Soeharto Beyond Indonesia.
Dengan demikian buku ini semakin menegaskan bahwa Orde Baru memang bukan hanya sekedar sosok individu, seperangkat lembaga, atau sekelompok pejabat. Karena itu upaya untuk mendemokratiskan Indonesia di masa mendatang berarti membongkar borok-borok sistemik yang biasa dilakukan oleh Sistem Orde Baru itu, meliputi politik teror, penghormatan berlebih, praktik suap-menyuap, dan sebagainya.
Sementara dalam konteks reformasi, buku ini mengingatkan kita semua agar masalah ketokohan seorang individu (entah itu Gus Dur, Megawati, Amien Rais, Akbar Tanjung, atau yang lain) hendaknya tidak terlalu ditonjolkan dalam rangka upaya-upaya menegakkan reformasi. Seperti ditengarai oleh Ignas Kleden dalam salah satu tulisannya, politik kita di masa reformasi ini ternyata ‘hanya berpindah dari politik aliran yang berorientasi ideologis ke politik karismatis yang berorientasi keunggulan pribadi.’ Buku ini mengajak kita untuk berdamai dengan urusan konflik antar-elit (baca: antar-tokoh politik) dengan lebih memilih kerja-kerja konstruktif dan bersifat struktural ketatanegaraan (pengelolaan negara).
Buku yang terdiri dari 12 bab ini hampir semuanya ditulis oleh para pengamat asing ternama: R. William Liddle, Robert Hefner, Donald K. Emmerson, Robert Cribb, Virginia M. Hooker, dan sebagainya.
Ulasan buku ini boleh dikatakan cukup tuntas karena berusaha menelusuri proses-proses sosiologis dan politik terbentuknya Sistem Soeharto. Pada bagian tertentu, ulasan dalam buku tidak mau melewatkan proses historis yang cukup panjang yang berperan penting dalam membentuk karakter sosial bangsa Indonesia—hingga merujuk pada masa sebelum penjajahan, seperti dalam tulisan Cribb dan Hefner. Kelebihan lainnya adalah keterkaitan sinergis antar-tulisan sehingga terkesan buku ini bukanlah buku kumpulan, melainkan buku utuh yang digarap secara serius.
Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, 28 Juli 2001.









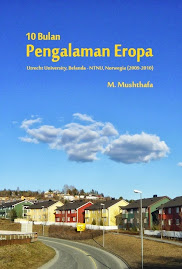




0 komentar:
Posting Komentar